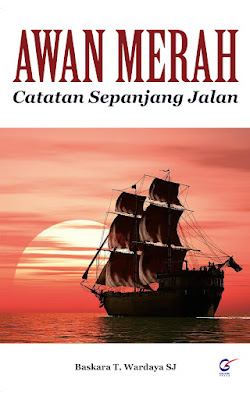oleh Indro Suprobo
Kisah tentang perempuan yang dituduh berzinah, yang terdapat di dalam Injil Yohanes 7:53-8:11, sangat menarik untuk dibaca sebagai kerangka memahami relasi politik antara Palestina dan Israel. Saya meyakini bahwa cara membaca kisah ini yang kemudian digunakan sebagai kerangka untuk membaca relasi politik antara Palestina dan Israel, belum pernah dilakukan oleh siapapun. Cara membaca yang demikian ini, saya sengaja dan saya sadari sebagai sebuah upaya penafsiran teologi politik. Teologi politik di sini dipahami sebagai sebuah refleksi teologis, yakni menemukan nilai atau prinsip-prinsip teologis terutama dari teks Kitab Suci, yang digunakan untuk merangi analisis relasi politik kontekstual dalam kehidupan sosial. Nilai dan prinsip teologis yang ditemukan itu pada gilirannya dijadikan landasan untuk menentukan sikap dan pilihan tindakan berhadapan dengan realitas sosial kontekstual yang dihadapi. Maka teologi politik adalah sebuah refleksi teologis yang digunakan sebagai inspirasi untuk membaca relasi-relasi sosial politik kontekstual. Dari sana dirumuskan pilihan-pihan sikap dan pilihan tindakan. Pilihan sikap dan pilihan tindakan yang dirumuskan ini menjadi cerminan dari apa yang disebut sebagai preferential option.
Teks dan Konteks
Teks lengkap kisah perempuan yang dituduh berzinah itu pantas dicermati secara detail dan ditempatkan dalam konteks, agar keseluruhan teks itu dapat dibaca secara lebih lengkap dan bertanggung jawab. Teks lengkapnya saya kutipkan sebagai berikut ini:
7:53 Lalu mereka pulang, masing-masing ke rumah-nya, 8:1 tetapi Yesus pergi ke bukit Zaitun. 8:2 Pagi-pagi benar Ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepada-Nya. Ia duduk dan mengajar mereka. 8:3 Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada-Nya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zinah. 8:4 Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus: «Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zinah. 8:5 Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapat-Mu tentang hal itu?» 8:6 Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan-Nya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-Nya di tanah. 8:7 Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada-Nya, Iapun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka: «Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.» 8:8 Lalu Ia membungkuk pula dan menulis di tanah. 8:9 Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. 8:10 Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya: "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" 8:11 Jawabnya: "Tidak ada, Tu(h)an." Lalu kata Yesus: "Akupun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang."
Sangat pantas dan sangat penting untuk dikemukakan bahwa perikop Yoh 7:53-8:11 merupakan sambungan dari perikop sebelumnya, yakni kisah tentang Pembelaan Nikodemus terhadap Yesus (7:45-52). Perikop tentang pembelaan Nikodemus ini sangat pantas dipertimbangkan dan dicermati sebagai bagian dari konteks karena ia memberi keterangan yang penting bagi detail ayat dalam kisah tentang perempuan yang dianggap berzinah ini. Seluruh kisah tentang perempuan yang dituduh berzinah ini wajib dibaca dalam kaitan dengan perikop tentang pembelaan Nikodemus, terutama memperhatikan ayat-ayat pada bagian 7:50-52, yang mendahului kisah ini, yang narasinya sebagai berikut:
7:50 Nikodemus, seorang dari mereka, yang dahulu telah datang kepada-Nya, berkata kepada mereka: 7:51 "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang, sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuat-Nya?" 7:52 Jawab mereka: "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah Kitab Sui dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea."
Gugatan Nikodemus kepada elit-elit Yahudi yang ingin menghukum Yesus tanpa terlebih dahulu mendengarkan dan mengetahui apa yang dilakukannya, sebagaimana terbaca pada ayat 7:51, menjadi kerangka motivasi untuk mengajukan kasus tentang perempuan yang dituduh berzinah itu. Secara jelas, kerangka motivasi itu ditegaskan dalam ayat 8:6 yang bunyinya "Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan-Nya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-Nya di tanah." Ini berarti bahwa pengajuan kasus tentang perempuan yang dituduh berbuat zinah itu secara keseluruhan sebenarnya merupakan sebuah konstruksi untuk menjebak Yesus sehingga jawaban Yesus itu dapat dikategorikan sebagai perkataaan dan perbuatan yang selanjutnya dijadikan landasan untuk menghukumnya, atau secara lebih tepat, agar mereka dapat menuntut pertanggungjawaban dari Yesus. Dengan demikian, relasi antara ayat 7:51 dan ayat 8:6 merupakan relasi yang sangat penting dan mendasar, serta menjadi kerangka dari seluruh persoalan yang diajukan di dalam perikop tentang perempuan yang dituduh berzinah ini.
Dalam konteks itu, perhatian utama dari seluruh narasi perikop ini harus diarahkan kepada relasi antara konstruksi pengajuan kasus dan jawaban serta sikap Yesus terhadapnya. Dari relasi antara kedua hal itulah, seluruh kemungkinan inspirasi dapat ditemukan dan dijadikan sebagai prinsip-prinsip dan nilai teologis yang penting. Selanjutnya, prinsip dan nilai teologis ini menjadi landasan bagi perumusan prefential option baik dalam wujud cara berpikir, cara bersikap maupun tindakan.
Analisis Narasi
Pertama, seperti dinyatakan dalam bagian konteks, persoalan tentang perzinahan yang dituduhkan kepada perempuan ini adalah sebuah konstruksi kasus. Jika dicermati secara lebih kritis, konstruksi ini tiba-tiba telah menyuguhkan sesuatu yang seolah-olah telah menjadi fakta atau realitas bahwa perempuan yang digelandang itu adalah perempuan yang didapati telah berbuat zinah. Tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan dan membela situasi dirinya sendiri, perempuan ini sudah langsung dikonstruksikan sebagai perempuan yang telah berbuat zinah, digelandang beramai-ramai, dilucuti kehormatan dan martabatnya sebagai pribadi. Ia langsung ditempatkan dalam tuduhan, dan dipaksa tunduk kepada konstruksi yang dirumuskan oleh para elit, lalu dengan seluruh kuasa dan dominasinya, para elit ini telah mengambil tindakan "penggelandangan" secara beramai-ramai, yang pada dirinya juga sudah merupakan bagian dari tindakan memberikan hukuman secara sosial karena perempuan itu telah langsung didiskreditkan. Suara dan haknya untuk menjelaskan dan membela dirinya langsung dibungkam. Konstruksi wacana tentang perzinahan yang telah dituduhkan kepadanya itu, serta merta telah langsung menjadi wacana sosial yang kurang lebih dipercayai oleh publik, paling tidak oleh segerombolan orang yang bersama-sama dengan para elit itu telah menggelandang perempuan itu dan menempatkannya sebagai terhukum. Dalam situasi ini, perempuan itu telah langsung terdiskriminasi secara wacana. Maka, wacana yang dikonstruksi oleh elit bahwa perempuan itu telah melakukan perzinahan, tanpa disertai penjelasan dan pembelaan terhadap fakta yang sebenarnya, telah menjadi suatu wacana diskriminatif atau discriminatory discourse.
Kedua, praktik konstruksi wacana tentang perzinahan yang disertai dengan tindakan penggelandangan terhadap perempuan ini, melanggar hukum Musa, terutama seperti yang tertulis di dalam kitab Ulangan 22:22 yang menyatakan bahwa,”apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati, laki-laki yang tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel”. Dalam konstruksi kasus ini, yang diajukan sebagai tertuduh yang pantas dihukum hanyalah perempuan, sementara pihak laki-laki yang terlibat dalam perzinahan ini sama sekali tak diajukan dan tak disinggung sedikitpun oleh para elit tersebut. Dalam konteks ini, ada semacam manipulasi informasi yang dilakukan demi memfasilitasi kepentingan, yakni kepentingan untuk menjebak Yesus. Ini berarti ada informasi yang disembunyikan agar konstruksi wacana tentang perzinahan itu menjadi wacana yang dominan yang langsung mendorong persetujuan publik tanpa sikap kritis, sehingga secara spontan dan emosional, publik langsung mendukung menyetujui konstruksi tersebut dan mendukung seluruh cara berpikir, cara bersikap dan cara bertindak kaum elit itu terhadap perempuan yang dituduh dan digelandangnya. Dalam kajian wacana kritis, tindakan kaum elit ini merupakan sebuah upaya untuk menghidupkan ilusi Muller Lyer publik di mana sisi-sisi emosional lebih dominan dan cenderung menjadi acuan sikap dan tindakan daripada sisi-sisi rasional kritis yang berbasis analisis informasi dan fakta. Ilusi Muller Lyer yang lebih mengacu kepada sisi-sisi emosional ini dimaksudkan untuk mengakumulasi dukungan terhadap seluruh konstruksi wacana dan tindakan kaum elit. Sekali lagi hal ini diperkuat oleh tertutupnya ruang dan kesempatan bagi perempuan itu untuk menjelaskan dan membela dirinya. Seluruh konstruksi dan tindakan kaum elit ini telah menjadikan perempuan itu sebagai pribadi yang dibungkam dan disudutkan dalam ketakberdayaan. Akibatnya, tak ada counter wacana.
Ketiga, inilah yang paling penting, yakni jawaban dan sikap Yesus terhadap seluruh konstruksi dan tindakan yang diajukan kepadanya. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat 8:6, menghadapi semua itu, Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-Nya di tanah. Dalam penafsiran saya, sebenarnya Yesus tak menulis apapun atau melukis apapun di tanah. Gerakan jarinya di atas tanah itu sebenarnya bukanlah sebuah tindakan menulis sesuatu atau melukis sesuatu, melainkan suatu ekspresi spontan dari sebuah sikap kritis yang sangat serius dan pengambilan jarak terhadap konstruksi wacana dan tindakan yang sedang dihadapinya. Ini merupakan ekspresi dari tindakan menimbang-nimbang, discernment, membaca fenomena, menganalisis, membongkar, dan menelusuri kemungkinan fakta-fakta yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan. Membungkuk dan menulis dengan jarinya di atas tanah adalah sebuah langkah radikal dan fundamental dalam menghadapi semua bentuk konstruksi wacana. Membungkuk adalah tindakan mengalihkan fokus bukan kepada apa yang tampak, yang formal, bentuk-bentuk, informasi dan rumusan bahasa yang beredar, melainkan kepada apa yang sebenarnya memengaruhi seluruh konstruksi itu, apa yang ada di balik yang tampak itu, apa yang tersembunyi di dalam yang formal dan bentuk-bentuk, serta apa yang tersembunyi di dalam informasi dan bahasa yang disuguhkan. Tindakan membungkuk atau mengalihkan fokus adalah sebuah tindakan yang mencerminkan independensi cara berpikir dan otonomi untuk mencermati realitas sehingga dapat benar-benar mengambil pilihan sikap dan cara bertindak yang tepat dan bertanggung jawab. Ini adalah tindakan membebaskan diri dari jebakan-jebakan yang dapat memengaruhi cara berpikir, cara bersikap dan cara bertindak. Ini adalah tindakan untuk membebaskan diri dari segala ideologi yang tersembunyi di dalam bahasa yang disuguhkan kepadanya.
Pantas dibayangkan bahwa saat Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di atas tanah, adalah saat hening, diam, tenang, sunyi. Itu adalah saat yang menggelisahkan bagi mereka yang terbiasa larut dalam hiruk pikuk kerumunan dan tak terbiasa dengan keheningan. Pantas dimengerti bahwa dalam situasi yang demikian itu, mereka akan terus-menerus bertanya, dalam hiruk pikuk dan kegelisahan (8:7). Boleh juga dipahami bahwa bombardir pertanyaan yang terus-menerus tiada henti adalah strategi untuk menguasai pikiran dan melemahkan daya kritis, atau sebuah teror terhadap nalar kritis.
Namun, dengan cara itu, Yesus telah sanggup melihat ketidakadilan yang tersembunyi di dalam bahasa tuduhan yang diajukan. Ia mengidentifikasi kepentingan yang sangat jelas di balik semua dalih yang seolah-olah menjunjung tinggi moralitas. Ia menemukan secara jeli motif-motif tersembunyi yang sebenarnya merupakan hasrat untuk mengukuhkan dominasi. Ia membaca dengan penuh waspada segala kelit kelindan yang sebenarnya merupakan keresahan untuk mempertahankan kuasa.
Dalam semua itu Yesus menyadari bahwa perempuan yang digelandang dalam hiruk pikuk keramaian gerombolan itu, adalah pribadi yang seluruh martabat dan harga dirinya sedang dilucuti. Oleh karena itu secara tegas akhirnya ia memberikan jawaban,"Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Pernyataan ini dapat diartikan bahwa siapapun yang telah sungguh-sungguh melakukan keadilan, tak memiliki kepentingan di balik dalih moralitas, tak memiliki hasrat tersembunyi untuk mendominasi, dan tak memiliki kegelisahan untuk mempertahankan kekuasaan, memiliki legitimasi penuh untuk memberikan hukuman. Karena jawaban Yesus ternyata sama sekali keluar jauh dari segala konstruksi dan jebakan, dan barangkali sama sekali tak sesuai dengan dugaan yang diharapkan, maka satu per satu mereka pergi meninggalkan perempuan itu sendirian. Jawaban yang di luar dugaan itu, sama sekali tak dapat dijadikan sebagai landasan untuk memfasilitasi kepentingan.
Jawaban Yesus bukanlah jawaban yang bersifat netral, melainkan jawaban yang loyal dan berpihak kepada nilai keadilan. Oleh karenanya, ia juga berpihak kepada yang cenderung rentan menjadi korban, yang posisinya didominasi dan terdiskriminasi. Yesus berpihak kepada perempuan dan membebaskannya dari ketidakadilan, melepaskannya dari kebungkaman, lalu memberi ruang kepadanya untuk bersuara (breaking the silence), sambil mewanti-wanti "pergilah dan jangan sampai tergelincir dalam jebakan-jebakan lagi."
Palestina dan Perempuan
Selama berpuluh-puluh tahun, dan terutama akhir-akhir ini, Palestina telah selalu diduduki, rumah-rumah tinggal warganya dihancurkan, penghuninya diintimidasi dan dipaksa mengungsi, mereka yang masih tinggal didiskriminasi, dihinakan martabatnya, ketika berada dalam perjalanan ditembak begitu saja dan dianggap bukan manusia. Hari-hari ini, warga Palestina sangat menderita, dibombardir dengan beragam bom dan peluru, habitat hidupnya dihancurkan menjadi puing-puing yang mengubur anak-anak dan perempuan tanpa dosa. Mereka kehilangan orang-orang tercinta. Anak-anak kehilangan orang tua, orang tua kehilangan anak-anak, kematian merenggut sanak-saudara. Sangat pantas disetujui bahwa setiap detik mereka menghadapi genosida.
Kekejaman dan ketidakadilan selama berpuluh-puluh tahun, tentu saja melahirkan mekanisme mempertahankan diri. Gerakan-gerakan perlawanan lahir di mana-mana. Ilan Pappe, seorang ahli sejarah Israel dan ilmuwan politik di Universitas Exeter Inggris menyatakan bahwa gerakan perlawanan di Palestina, pada awalnya dimulai oleh kaum kristen sekular Palestina lalu diikuti oleh banyak gerakan perlawanan lainnya, dan yang menjadi paling populer saat ini adalah Hamas. Ini berarti bahwa perlawanan warga Palestina bukanlah persoalan agama melainkan persoalan mempertahankan kehidupan dan kemanusiaan yang telah selalu dihancurkan dan dihinakan. Ini adalah persoalan mempertahankan harkat dan martabat kemanusiaan di hadapan tindakan kejahatan selama puluhan tahun.
Namun yang terjadi, hak untuk melakukan perlawanan demi mempertahankan harkat dan martabat kemanusiaan yang dihinakan dan dihancurkan itu, selalu dikonstruksikan sebagai terorisme. Konstruksi wacana yang menyatakan bahwa tindakan perlawanan itu adalah terorisme, telah memanipulasi fakta yang sesungguhnya terjadi. Konstruksi wacana itu juga telah melahirkan pandangan diskriminatif terhadap warga Palestina sehigga ketika mereka menghadapi kejahatan kemanusiaan dan genosida, mereka justru ditempatkan sebagai pihak yang bersalah dan pantas menanggung hukuman. Tak mengherankan jika ada banyak negara yang kuat dan besar, yang memiliki pengaruh dalam percaturan politik dunia, justru mendukung pihak yang melakukan penghancuran kemanusiaan dan genosida, melalui beragam kebijakan termasuk melalui dukungan persenjataan. Dengan demikian konstruksi wacana diskriminatif (discriminatory discourse) itu telah benar-benar beroperasi dan memengaruhi cara berpikir, cara bersikap serta cara bertindak begitu banyak orang. Tindakan-tindakan kejahatan dan ketidakadilan telah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga seolah-olah tampak sebagai tindakan penuh kewibawaan moral. Manipulasi itu juga mengakibatkan pihak yang melakukan ketidakadilan dan kejahatan itu justru menilai diri dan dinilai oleh para pendukungnya sebagai aktor penegak moralitas yang memiliki hak untuk memberikan hukuman.
Dalam situasi ini, Palestina menjadi seperti perempuan yang dituduh berzinah di dalam narasi Injil Yohanes 7:53-8:11. Tanpa diberi ruang untuk menjelaskan dan membela dirinya, Palestina telah digelandang selama puluhan tahun, dihinakan, martabat kemanusiaannya dihancurkan. Pengeboman rumah sakit, penghancuran tempat tinggal, serangan terhadap tempat-tempat pengungsian yang mengakibatkan kematian ribuan nyawa termasuk anak-anak dan perempuan, penutupan seluruh akses bantuan, pemblokiran akses terhadap seluruh kebutuhan dasar yang vital, adalah tindakan penggelandangan terhadap Palestina, yakni penghukuman publik sebelum ia sendiri dapat menjelaskan dan membela dirinya sendiri. Seperti perempuan dalam kisah itu, Palestina telah disudutkan seolah-olah sebagai manusia paling berdosa sehingga pantas diajukan ke hadapan publik untuk segera ditentukan hukumannya. Dalam seluruh proses itu, ia telah dibungkam, sama sekali tak diberi ruang untuk menyatakan diri dan menyatakan fakta dan pengalaman yang senyatanya dihadapi.
Membungkuk dan menulis dengan jari di atas tanah
Menghadapi semua itu, satu-satunya tindakan yang pantas kita lakukan, seperti dilakukan oleh Yesus, adalah membungkuk dan menulis dengan jari di atas tanah. Kita wajib mengalihkan perhatian dari konstruksi wacana diskriminatif yang diajukan itu, lalu seperti dipesankan oleh Hannah Arendt, kita perlu membangun imajinasi tentang liyan, yakni imajinasi tentang menjadi orang Palestina. Membungkuk dan menulis dengan jari di atas tanah adalah praktik tentang sikap kritis, discernment, menelusuri fakta-fakta dan realitas yang sebenarnya terjadi, membaca fenomena, menganalisis, membongkar, dan menelusuri kemungkinan fakta-fakta yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan, membongkar ideologi dan kepentingan yang tersembunyi di dalam bahasa yang digunakan, menyelami pengalaman konkrit yang dirasakan oleh orang-orang Palestina dalam menghadapi fakta-fakta dan realitas itu, menerapkan seluruh pengalaman, duka, kecemasan, penderitaan, perasaan kehilangan, pengalaman ketergantungan, pengalaman pengungsian, kengerian menyaksikan kematian bertubi-tubi tanpa dapat menyelamatkan diri, selalu berjaga-jaga namun selalu diikuti oleh bahaya yang datang tiba-tiba lalu menghancurkan apapun yang ada. Selanjutnya, menempatkan seluruh pengalaman itu sebagai pengalaman diri, untuk meneliti dan mencermati, bagaimanakah gerak batin di dalam diri sendiri. Upaya membungkuk dan menulis dengan jari di atas tanah ini, niscaya akan membawa kita kepada penemuan bahwa sejatinya seluruh pengalaman yang dihadapi oleh orang-orang Palestina ini adalah pengalaman ketidakadilan yang nyata, dan pengalaman menghadapi penghancuran kemanusiaan dalam beragam cara.
Gustavo Gutierrez, seorang teolog pembebasan Amerika Latin dari Peru, menyatakan bahwa di hadapan ketidakadilan dan penindasan, apalagi yang didukung oleh konstruksi wacana diskriminatif, sikap netral tidak memiliki tempat, sebab sikap netral justru sama artinya dengan mendukung para penindas. Menghadapi kenyataan ketidakadilan dan penindasan, orang musti berpihak dan loyal kepada nilai keadilan, yang diwujudkan di dalam praksis preferential option for the oppressed, memihak dan membela mereka yang ditindas. Sikap ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus dalam kisah perempuan itu, yakni berpihak kepada keadilan dengan cara memihak dan membela perempuan yang dituduh berzinah, menyelamatkan dan membebaskan perempuan itu dari kesewenang-wenangan kaum elit yang memperalatnya demi kepentingan mereka sendiri.
Dengan demikian, pernyataan Yesus yang berbunyi "Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu" dalam konteks ketidakadilan dan penindasan terhadap Palestina dapat dirumuskan ulang demikian "Barangsiapa di antara kamu sama sekali tak pernah melakukan tindakan teror, penggusuran, pengusiran, penghancuran, memaksa orang untuk mengungsi, menghancurkan rumah sakit dan membunuh anak-anak, perempuan dan orang-orang yang tak bersalah, menutup seluruh akses kebutuhan vital yang sangat penting bagi kehidupan, tak menjalankan politik apartheid, rasisme dan genosida terhadap siapapun, hendaklah ia melempar batu kepada orang-orang Palestina". Namun, jika tidak demikian, maka siapapun dia, sama sekali tak memiliki legitimasi untuk menghakimi dan menghukum orang-orang Palestina.
Dalam konteks ini, upaya dan tindakan tegas untuk menghentikan seluruh pendudukan, penyerangan, penghancuran, dan bombardir peluru terhadap Palestina adalah sebuah kewajiban dan tuntutan serta panggilan kemanusiaan bagi siapapun yang berakal sehat. Seperti dikatakan oleh Bhikku Shri Pannavaro Mahatera bahwa penderitaan orang lain itu semestinya menggetarkan dan mendorong orang untuk memberikan bantuan, jika tak dapat melakukan apapun, paling tidak mendoakan agar mereka segera dibebaskan dari penderitaan, demikian juga Johann Baptist Metz, seorang teolog politik Jerman, menyatakan bahwa penderitaan orang lain merupakan undangan bagi orang beriman untuk membebaskan diri dari segala bentuk ketidakpedulian. Terbebas dari ketidakpedulian itulah yang disebut sebagai compassion. Keberpihakan dan pembelaan terhadap mereka yang senyatanya tertindas, dipaksa mengungsi, dihancurkan, dan menghadapi ancaman kematian dalam hitungan detik, adalah wujud nyata dari ketergetaran dan compassion.
Jika tak memiliki kesanggupan untuk secara langsung menghentikan penindasan yang masih terus berlangsung ini, paling tidak kita masih dapat menghentikan konstruksi wacana diskriminatif tentang Palestina dengan selalu memproduksi counter wacana bahwa Palestina adalah warga manusia yang memiliki hak untuk hidup dalam damai, bertumbuh dalam adab yang bernilai dan luhur sebagaimana sudah dipraktikkan sejak dahulu kala, bahwa perlawanan-perlawanan mereka yang diwakili oleh kelompok pejuang Hamas bukanlah terorisme pada dirinya sendiri melainkan sebuah keterpaksaan yang dipilih sebagai upaya satu-satunya untuk membela dan mempertahankan martabat kemanusiaan yang selalu saja dihancurkan dan direndahkan. Sudah saatnya ruang-ruang yang luas dan bebas bagi Palestina untuk bersuara dan mengungkapkan dirinya tentang realitas yang dihadapinya setiap hari, diberikan dan disediakan. Melalui konstruksi-konstruksi wacana yang empatik dan penuh solidaritas terhadap Palestina, kita dapat bersama-sama melakukan upaya edukatif, konstruktif dan kritis sebagaimana dilakukan oleh banyak orang Israel sendiri, terutama para mantan tentara IDF, yang didukung oleh banyak orang Yahudi terdidik yang berpikiran kritis dan berwawasan luas, yakni "breaking the silence", memecah kebisuan dan menyuarakan kebenaran.
Semoga Palestina segera terbebas dari penderitaan dan penindasan, lalu meraih martabatnya yang luhur sebagai manusia merdeka. Semoga kesaksian hidup mereka, yang telah sekian lama dididik oleh gelapnya penderitaan, pada akhirnya berkilau dan memancar bagaikan bunga bagi segala kota, Zahrat al-Mada'en.***